Madinah Fadhilah: Politik Kenabian dan Etika Akal dalam Negara Ideal Al-Farabi
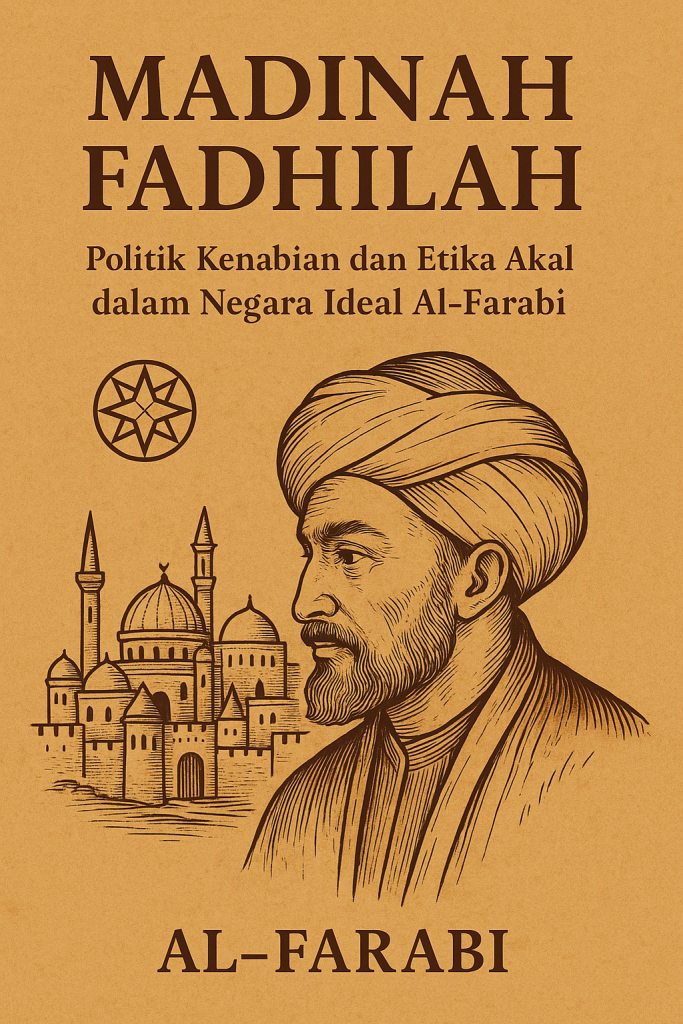
Oleh: MJ.Wijaya
NU SUDRA
Harian Kuningan – Di tengah retorika demokrasi yang kian riuh namun hampa arah etis, kita layak menengok kembali visi klasik tentang negara ideal yang lahir dari rahim filsafat Islam. Al-Farabi, sang Guru Kedua dalam tradisi filsafat Islam—setelah Aristoteles—menawarkan sebuah magnum opus berjudul Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah (Pandangan Masyarakat Kota Utama), yang tidak hanya menjadi warisan spekulatif politik, melainkan juga risalah moral tentang manusia, akal, dan tatanan masyarakat yang ditopang oleh kebajikan.
Kitab ini bukan sekadar imitasi dari The Republic Plato. Al-Farabi menyintesis antara filsafat Yunani dan wahyu Islam dalam satu kerangka ontologis yang utuh. Ia menempatkan filsafat politik dalam hubungan erat dengan metafisika dan psikologi manusia. Maka, membedah Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah tidak cukup hanya dengan pendekatan politik normatif, melainkan harus ditempuh melalui pisau hermeneutik yang menelusuri gagasan tentang akal, jiwa, dan kenabian dalam struktur ideal negara.
Negara sebagai Cermin Kosmos
Bagi Al-Farabi, negara bukan sekadar entitas hukum dan kekuasaan. Ia adalah mikro-kosmos dari tatanan alam semesta. Dalam struktur metafisisnya, realitas bertingkat dari Tuhan (al-wajib al-wujud) turun melalui intelek-intelek aktif hingga ke alam fisik. Dalam struktur sosial, hal serupa terwujud dari pemimpin utama yang serba sempurna hingga masyarakat yang tunduk dan saling menopang.
Negara ideal—al-Madinah al-Fadilah—adalah tempat di mana tatanan akal, kebajikan, dan wahyu berpadu. Pemimpinnya adalah pribadi paripurna: ia adalah filsuf, nabi, dan negarawan sekaligus. Ia memahami realitas tertinggi melalui akalnya dan menuntun masyarakat dengan hukum-hukum yang bersumber dari pengetahuan ilahiah. Dengan kata lain, politik dalam pemikiran Al-Farabi bukanlah perebutan kekuasaan, tetapi manifestasi dari visi profetik.
Pemimpin: Filsuf atau Nabi?
Salah satu tesis paling radikal dari Al-Farabi adalah identifikasi pemimpin ideal dengan nabi sekaligus filsuf. Ia menyatakan bahwa pemimpin Madinah Fadilah harus memiliki dua kekuatan utama: kekuatan intelektual (untuk mengetahui realitas universal) dan kekuatan imajinatif (untuk mentransformasikan realitas itu dalam bentuk simbol, syariat, dan hukum).
Di sinilah kenabian menjadi bagian dari filsafat politik. Nabi, dalam pandangan Al-Farabi, adalah manusia yang akalnya menyatu dengan ‘aql fa‘al (akal aktif) sehingga mampu menangkap realitas non-material dan kemudian menyampaikannya dalam bentuk wahyu. Dalam konteks negara, wahyu menjadi dasar moral dan hukum publik.
Maka, pemimpin sejati bukanlah produk elektoral atau teknokrasi, melainkan jiwa paripurna yang telah menempuh jalan akal dan memiliki kapasitas profetik.
Madinah-Madinah yang Rusak
Sebagai kontras, Al-Farabi juga mengidentifikasi berbagai jenis negara yang menyimpang dari Madinah Fadilah. Ia menyebutnya sebagai al-mudun al-jahilah (kota-kota bodoh), al-mudun al-fasiqah (kota-kota durhaka), dan al-mudun al-dallah (kota-kota sesat).
Negara bodoh adalah negara yang menolak kebaikan hakiki dan hanya mengejar kenikmatan material. Negara durhaka adalah yang tahu tentang kebaikan tetapi menolaknya secara sadar. Negara sesat adalah yang mengikuti pemimpin yang sesat secara metafisis, seperti yang mengklaim kenabian tanpa kualifikasi akal dan wahyu.
Jika kita tarik ke realitas kontemporer, maka banyak negara modern hari ini—termasuk negara-negara Muslim—lebih menyerupai al-mudun al-jahilah. Negara yang memburu pertumbuhan ekonomi tanpa etika, mengagungkan kebebasan tanpa orientasi moral, dan menjadikan pemimpin sebagai figur populer tanpa akal paripurna.
Aktualitas Gagasan Al-Farabi
Gagasan negara ideal Al-Farabi memang utopis. Namun sebagaimana Plato dan semua pemikir besar dalam sejarah filsafat, utopia diperlukan bukan untuk direalisasikan sepenuhnya, melainkan sebagai horizon nilai untuk menilai realitas.
Di era ketika demokrasi telah direduksi menjadi perayaan suara mayoritas tanpa kebijaksanaan, Al-Farabi mengingatkan kita bahwa negara bukan sekadar agregasi kehendak publik, melainkan organisasi etis yang diarahkan oleh akal dan kebajikan.
Di saat ketika pemimpin dipilih berdasarkan popularitas alih-alih kapabilitas, Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah menjadi suara kuno yang menyerukan kembali pentingnya filsafat sebagai dasar kepemimpinan.
Dan di zaman ketika agama sering dijadikan alat politik, Al-Farabi menunjukkan bahwa kenabian bukanlah kekuasaan, tetapi iluminasi akal yang melayani tatanan dan kebaikan universal.
Al-Farabi mungkin hidup di abad ke-10, namun tantangan yang ia jawab tetap hidup hingga hari ini. Maka tugas kita bukan sekadar membaca kitabnya, melainkan menjadikannya cermin untuk melihat betapa jauhnya kita dari negara yang berakal.
Alas mentaok.
8 Mei 2025
