Flourishing dan Human Flourishing: Jalan Filosofis Menuju Kehidupan Bermakna
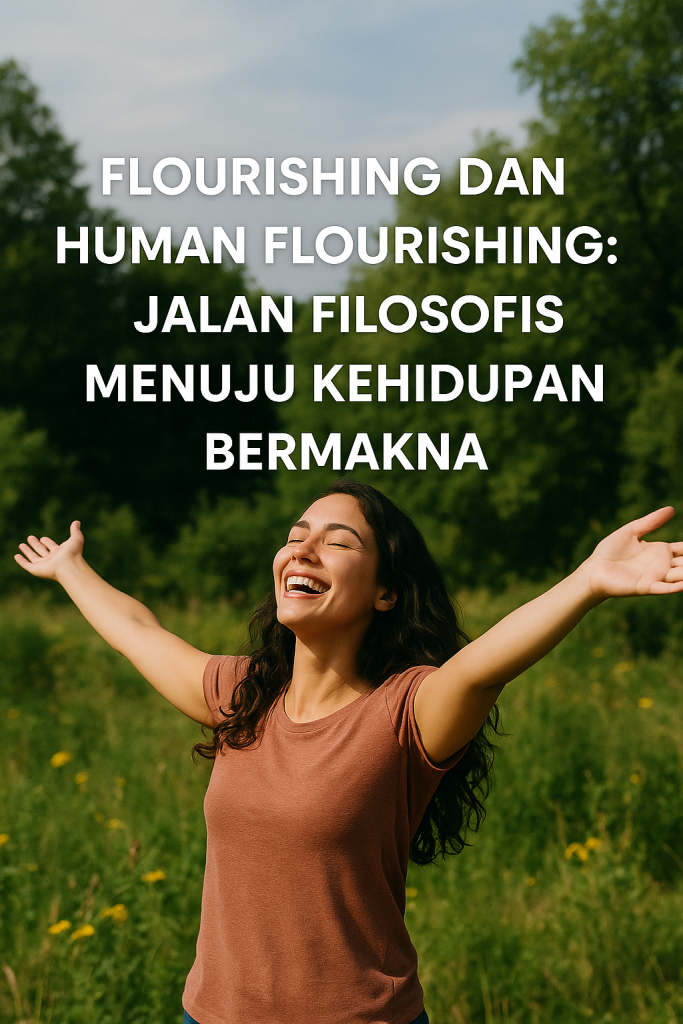
Oleh: MJ.Wijaya.
NU SUDRA
Harian Kuningan – Dalam era modern yang ditandai oleh percepatan teknologi, kompetisi ekonomi, dan individualisme, perbincangan tentang flourishing atau kebermakmuran eksistensial menjadi semakin relevan. Istilah flourishing merujuk pada kondisi manusia yang bukan sekadar hidup, tetapi hidup dengan baik—sebuah keadaan di mana potensi manusia tumbuh secara optimal dalam ranah moral, intelektual, sosial, dan spiritual. Gagasan ini telah lama menjadi pusat diskursus dalam filsafat moral dan psikologi positif, mencerminkan upaya manusia memahami arti dari kehidupan yang baik (eudaimonia), kebahagiaan sejati, dan kebermaknaan yang tahan uji oleh waktu.
1. Dari Eudaimonia ke Flourishing: Akar Filosofis
Konsep flourishing memiliki akar kuat dalam filsafat Yunani kuno, terutama melalui pemikiran Aristoteles. Dalam Nicomachean Ethics, Aristoteles menyatakan bahwa tujuan akhir manusia adalah eudaimonia, yang sering diterjemahkan sebagai “kebahagiaan,” namun lebih tepat dimaknai sebagai “flourishing” atau “kehidupan yang berhasil.” Baginya, eudaimonia dicapai melalui aktivitas rasional yang dijalankan secara penuh dalam kebajikan (aretē).
“The good for man is an activity of the soul in accordance with virtue, in a complete life.” – Aristoteles, Nicomachean Ethics
Aristoteles menolak pandangan hedonistik yang menyamakan kebahagiaan dengan kenikmatan sesaat. Ia menekankan bahwa flourishing hanya mungkin bila manusia hidup secara etis, menggunakan nalar, dan berpartisipasi dalam komunitas politik yang adil. Dengan demikian, flourishing tidak bersifat individualistik, melainkan intrinsik terkait dengan hubungan sosial dan peran publik.
2. Human Flourishing dalam Psikologi Positif
Dalam psikologi modern, konsep flourishing diperluas oleh tokoh seperti Martin Seligman, bapak positive psychology, yang membangun teori PERMA (Positive emotion, Engagement, Relationships, Meaning, Accomplishment) sebagai kerangka kerja bagi human flourishing. Berbeda dengan pendekatan psikologi klinis yang fokus pada penyakit, Seligman menekankan pertumbuhan, kekuatan, dan makna.
“Flourishing is the product of the pursuit and engagement of an authentic life that brings inner joy and happiness through meeting goals, being connected with life passions, and relishing in accomplishments through the peaks and valleys of life.” – Martin Seligman
Namun, pendekatan psikologis ini tetap membuka pertanyaan filosofis: apakah flourishing semata-mata akumulasi kondisi psikologis positif, ataukah ia mensyaratkan visi moral dan etis tertentu tentang manusia?
3. Human Flourishing dan Etika Kontemporer
Dalam filsafat kontemporer, konsep human flourishing sering digunakan dalam kerangka etika kebajikan (virtue ethics), khususnya oleh tokoh seperti Alasdair MacIntyre. Dalam After Virtue, MacIntyre menyatakan bahwa kehidupan bermakna hanya mungkin dalam konteks narasi dan praktik sosial yang bernilai. Ia mengkritik fragmentasi moral modern yang memutus hubungan antara individu dan tradisi etis komunal.
“A virtue is an acquired human quality the possession and exercise of which tends to enable us to achieve those goods which are internal to practices…” – Alasdair MacIntyre
Dalam konteks ini, human flourishing tidak bisa dilepaskan dari keutamaan moral, peran dalam komunitas, dan keterlibatan dalam praktik yang bermakna secara historis dan sosial.
4. Spiritualitas dan Transendensi dalam Flourishing
Tak kalah penting, dimensi spiritual juga hadir dalam konsep human flourishing, terutama dalam filsafat Timur dan teologi. Dalam tradisi Islam misalnya, falah (keberhasilan sejati) tidak hanya mencakup kebahagiaan duniawi, tetapi juga keselamatan dan kedamaian batin dalam kedekatan dengan Tuhan.
“Indeed, he succeeds who purifies his soul.” – Qur’an, Surah Ash-Shams (91:9)
Begitu pula dalam pemikiran Viktor Frankl, seorang psikiater dan filsuf eksistensial, flourishing terwujud melalui pencarian makna, bahkan dalam penderitaan. Frankl menulis bahwa manusia dapat bertahan dalam keadaan paling gelap sekalipun jika ia memiliki alasan untuk hidup.
“Those who have a ‘why’ to live can bear almost any ‘how.’” – Viktor E. Frankl
5. Tantangan Zaman Modern
Di tengah krisis lingkungan, kapitalisme hiper-modern, dan alienasi sosial, gagasan human flourishing menghadapi tantangan serius. Budaya performatif yang menekankan produktivitas sering kali justru menggerus nilai-nilai kontemplatif, relasi otentik, dan makna eksistensial. Dalam situasi ini, flourishing menuntut perlawanan terhadap logika instrumental yang mereduksi manusia menjadi alat produksi atau objek algoritma.
Penutup
Flourishing adalah wacana multidimensional yang menjembatani filsafat, psikologi, etika, dan spiritualitas. Ia mengajak kita melampaui hidup yang “cukup baik” menuju hidup yang “layak dijalani.” Di tengah dunia yang tergesa dan terpecah, diskursus ini menjadi ruang kontemplatif untuk menata ulang visi kita tentang manusia, makna, dan arah hidup.
Emperan UIN Sunan Kalijaga
6 mei 2025.
